Penulis: Muhammad Dudi Hari Saputra (Akademisi Universitas Kutai Kartanegara)
EXPRESI.co, KUTAI KARTANEGARA — Keadilan, sebuah kata yang memiliki resonansi mendalam dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia, disebut dua kali dalam Pancasila: “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam Pembukaan UUD 1945, keadilan dilekatkan dengan nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar prinsip hukum atau politik, tetapi bagian dari nurani bangsa dan jiwa manusia itu sendiri.
Spirit keadilan inilah yang mendorong segenap elemen pemuda, akademisi, dan masyarakat Kalimantan Timur untuk terus memperjuangkan hak atas pengelolaan Blok Mahakam, sebagai salah satu blok migas paling strategis dan produktif di Indonesia. Blok ini bukan sekadar ladang gas dan minyak, tetapi juga simbol kedaulatan energi dan distribusi keadilan fiskal yang selama ini timpang.
Sejarah dan Potensi Strategis Blok Mahakam
Blok Mahakam telah menjadi andalan eksplorasi dan eksploitasi migas nasional sejak awal 1970-an. Berdasarkan data KNPI Kaltim (2015), sepanjang 1970–2010, telah dieksploitasi sekitar 51,92% atau 13,5 triliun kaki kubik (tcf) cadangan gas, menghasilkan pendapatan bruto sekitar USD 100 miliar. Kini tersisa sekitar 48,18% cadangan (12,5 tcf), dengan potensi pendapatan yang diperkirakan mencapai USD 187 miliar atau setara dengan Rp 1.700 triliun.
Per 2025, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sebagai operator resmi mencatatkan rata-rata produksi sebesar 407 MMSCFD gas dan 21,9 MBOPD minyak, sesuai target rencana kerja dan anggaran tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa Blok Mahakam tetap menjadi tulang punggung energi nasional dan berperan vital dalam menjaga ketahanan migas Indonesia.
Alih Kelola dan Tantangan Regulasi
Pasca berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie pada akhir 2017, pengelolaan Blok Mahakam dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pusat melalui Pertamina. Sesuai amanat PP No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas, pemerintah pusat berhak atas pengelolaan 100% wilayah kerja, dengan Participating Interest (PI) sebesar 10% dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui BUMD.
Upaya ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, yang direspons positif karena melarang keterlibatan swasta dalam pengelolaan PI 10%, serta mewajibkan modal awal BUMD dibiayai oleh kontraktor (Pertamina). Namun, Permen tersebut juga menyisakan sejumlah kelemahan: ketidaksesuaian dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang membolehkan keterlibatan swasta, serta ketidakjelasan peran kepala daerah tingkat II (kabupaten/kota) dalam distribusi wilayah kerja dan pendapatan.
Regulasi Terkini: Permen ESDM No. 1 Tahun 2025
Pada awal 2025, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2025, yang menggantikan regulasi sebelumnya. Beleid baru ini menegaskan:
– Redefinisi BUMD: Hanya BUMD yang dimiliki penuh atau mayoritas oleh pemerintah daerah yang berhak mengelola PI 10%.
– Larangan penguasaan ganda: Satu BUMD hanya boleh mengelola satu WK PI 10%, untuk mencegah monopoli dan konflik kepentingan.
– Penetapan wilayah PI berdasarkan pelamparan reservoir: Melalui mekanisme ilmiah dan koordinasi gubernur serta bupati/walikota, dengan lembaga independen sebagai verifier.
– Modal awal tetap dibantu oleh kontraktor migas (misalnya Pertamina Hulu Mahakam), tanpa bunga dan dibayar melalui bagi hasil produksi.
– Pemberian sanksi tegas kepada BUMD yang tidak patuh, termasuk pencabutan hak PI 10%.
Permen ini mencerminkan semangat Pancasila dan Trisakti Bung Karno—berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Namun, tantangan tetap ada. Kepala daerah tingkat II masih belum memiliki kewenangan yang tegas, meskipun secara administratif dan geografis, daerah merekalah yang paling terdampak langsung oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.
Distribusi yang Tidak Adil: Kritik atas Sistem Fiskal
Ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah masih menjadi luka lama yang belum sembuh. Pada 2013, PDRB Kaltim tercatat sebesar Rp 425,4 triliun, namun transfer fiskal dari pusat ke daerah hanya sekitar Rp 36,2 triliun (8,51%). Angka ini masih konsisten di bawah 10% hingga 2024, sebuah bentuk ketidakadilan fiskal yang sangat mencolok.
Sementara daerah menanggung kerusakan lingkungan, sosial, dan infrastruktur akibat eksploitasi migas, manfaat ekonomi yang dinikmati masih dominan terserap oleh pusat dan korporasi besar. Model ketimpangan ini mencerminkan pola ekonomi dependensia, di mana daerah-daerah penghasil (periphery) menjadi pelayan kebutuhan energi dan fiskal pusat kekuasaan (core).
Refleksi Keadilan dan Masa Depan Energi Nasional
Tuntutan masyarakat Kaltim atas hak PI 10% bukan sekadar soal ekonomi, tetapi lebih dalam: ini adalah tuntutan atas keadilan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Keinginan agar blok Mahakam dan blok-blok lain dikelola oleh anak negeri bukan hanya pilihan pragmatis, tetapi juga ideologis—untuk menjadikan energi sebagai instrumen kemakmuran bersama, bukan alat eksploitasi elite dan investor asing.
Indonesia tidak hanya butuh sumber daya alam, tetapi juga kebijakan yang adil dan merata. Regulasi terbaru adalah langkah maju, tetapi belum final. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa semangat otonomi daerah, nawacita, dan pasal 33 UUD 1945 benar-benar diwujudkan dalam struktur kelembagaan, alokasi fiskal, serta pelibatan penuh pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota.
Menuju Indonesia yang Berkeadilan Energi
Perjuangan Blok Mahakam adalah simbol dari perjuangan yang lebih luas: tentang hak daerah atas sumber daya mereka sendiri, tentang keadilan dalam distribusi, dan tentang masa depan bangsa yang tidak lagi dikendalikan oleh ketimpangan struktural. Semoga pemerintah dan pemangku kepentingan mendengar suara dari pinggiran ini, yang sesungguhnya adalah suara dari inti nurani keadilan Indonesia. (*)
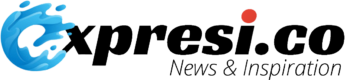







Tinggalkan Balasan